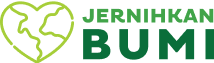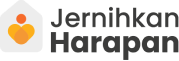Merevisi Paradigma Penyidikan: Dari Mencari Tersangka ke Menguji Dugaan

PENYIDIKAN dalam sistem hukum Indonesia saat ini kerap dipahami sebagai tahap formalitas yang secara otomatis diarahkan pada penetapan tersangka.
Padahal, tahapan ini seharusnya merupakan proses epistemologis di mana setiap asumsi awal—bahkan yang tampak kuat sekalipun—diteliti, diuji, dan, jika perlu, ditolak.
Sayangnya, definisi penyidikan dalam Pasal?1 angka?2 KUHAP masih berbunyi, “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.”
Secara implisit, definisi tersebut telah memasukkan “menemukan tersangka” sebagai tujuan akhir perjalanan hukum.
Pendekatan semacam ini sejatinya telah menciptakan kerangka berpikir yang bias, di mana proses penyidikan tidak lagi menjadi medan terbuka bagi penilaian objektif, melainkan arena pembenaran.
Baca juga: Penguatan Peran Advokat dalam Rancangan KUHAP: Dari Penyelidikan hingga Persidangan
Budaya ini turut didorong oleh tekanan kelembagaan, di mana keberhasilan seorang penyidik sering kali diukur dari jumlah tersangka yang berhasil ditetapkan, bukan dari akurasi dan keadilan proses.
Hasilnya, penyidikan lebih mirip manuver politik demi membungkus kasus agar cepat “tuntas”.
Konteks dan kritik epistemologis
Pada rapat dengar pendapat di Komisi III DPR, Kamis (19/6/2025), Pakar hukum pidana Chairul Huda menyoroti problem utama ini. Menurut dia, orientasi penyidikan semata-mata untuk menetapkan tersangka bukan saja sangat problematik, tetapi juga berbahaya.
Huda menyatakannya tegas: "Seolah-olah penyidikan itu ujungnya harus penetapan tersangka, padahal penyidikan bisa dua sisi, bisa menetapkan tersangka, bisa tidak."
Karena itu, ia mendorong agar definisi penyidikan dalam RUU KUHAP direvisi menjadi lebih netral—misalnya ditambahkan frasa “atau guna menetapkan bahwa peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau tidak cukup bukti sebagai tindak pidana.”
Imbauan ini bukan tanpa dasar. Studi epistemologi hukum modern mengingatkan bahwa proses mencari kebenaran tidak bisa berjalan linear dari teori awal sendiri.
Haack (2004) menekankan bahwa pendekatan hukum yang benar harus bersifat fallibilistik, yakni jujur terhadap ketidakpastian dan siap untuk mengoreksi kesalahan jika diperlukan.
Dalam penyidikan, hal ini berarti penyidik harus bersikap seperti ilmuwan: mengujikan dugaan awal dengan bukti tanpa prasangka, dan siap memutuskan bahwa tidak ada tindak pidana jika tidak ditemukan fakta hukum yang cukup.
Jika tidak, maka budayanya menjadi bias, memaksakan agenda ke ranah penegakan hukum.
Lebih dari itu, kajian psikologi forensik telah menemukan kecenderungan bias konfirmasi di lapangan—penyidik yang awalnya meyakini seseorang bersalah cenderung lebih fokus mencari bukti-bukti yang mendukung—seringkali mengabaikan bukti lain yang justru bisa membantah dugaan mereka.
Baca juga: Pemerintah Ungkap 9 Poin Penguatan di Dalam DIM RUU KUHAP