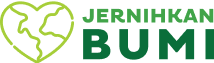Mens Rea: Jalan Menuju Keadilan

DI RUANG sidang itu, waktu tidak bergerak. Hukum membeku, mencatat, lalu mengadili. Namun, bukan semata peristiwa yang diadili. Juga bukan hanya akibat dari sebuah perbuatan. Melainkan sesuatu yang lebih sunyi: kehendak.
Kita menyebutnya mens rea. Dalam bahasa Latin, ia berarti “niat jahat”—a guilty mind. Lebih dari sekadar niat, ia adalah letupan batin manusia saat pilihan etis dibentuk oleh kehendak bebas.
Apakah seseorang bersalah karena melakukan sesuatu yang dilarang? Ataukah ia baru layak dipidana bila perbuatan itu dilakukan dengan kesadaran, kehendak, dan kehendak itu sendiri jahat?
Dalam perkara pidana, mens rea adalah penanda antara kekhilafan dan kejahatan. Ia adalah jantung dari teori pertanggungjawaban pidana.
Namun di negeri ini, kadang jantung itu diganti dengan kalkulasi: apakah negara rugi? Apakah prosedur dilompati?
Lalu niat—yang harusnya jadi pusat penghakiman—perlahan hilang dari panggung pengadilan.
Baca juga: Vonis 4,5 Tahun Tom Lembong: Terbaliknya Efek Jera
Sejarah hukum pidana tidak pernah bisa dilepaskan dari pencarian tentang niat. Dalam sistem Anglo-Saxon, niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) adalah dua sisi yang tak boleh terpisah.
Blackstone, dalam Commentaries on the Laws of England, menyebut bahwa hukum tak akan menghukum seseorang kecuali jika ia melakukan sesuatu dengan evil intent.
Di sistem Eropa Kontinental, konsep schuld atau kesalahan menjadi fondasi pemidanaan. Seseorang hanya bisa dihukum jika ada schuldvorm—bentuk kesalahan subjektif—baik itu kesengajaan (opzet) maupun kealpaan (culpa).
Tanpa kesalahan, tak ada pidana. Tanpa kehendak, tak ada moralitas hukum.
Namun, praktik hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia, kerap kali membelok. Kita sering mempidanakan akibat, bukan kehendak.
Kita menghitung kerugian, bukan membuktikan niat. Kita menimbang prosedur yang dilompati, bukan kesengajaan yang mengiringi. Dan dalam pembelokan itu, mens rea menjadi bayangan yang dilupakan.
Di satu sisi, pidana adalah alat untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang membahayakan.
Di sisi lain, ia adalah ekspresi paling keras dari kewenangan negara untuk menyentuh kebebasan seseorang.
Maka hukum pidana tak boleh gegabah. Ia memerlukan kepastian bahwa seseorang patut dipidana bukan hanya karena akibat, melainkan karena kesadaran batin atas perbuatannya.